Hak Asasi Manusia Menurut Paradigma Liberalisme, Realisme dan Konstruktivisme
Rabu lalu kelas HAM & Demokrasi tiba-tiba mengadakan pop quiz. I was like, fuck. Saya bener-bener ngga siap untuk berpikir apalagi menjawab soal kuis. In fact, malam itu niat saya adalah sekedar ingin tidur di kelas untuk mengurangi sakit kepala dan demam yang rasanya semakin menjadi. Jadi apa boleh buat, dengan segala tenaga yang tersisa, saya meniatkan untuk menjawab soal itu sekenanya lalu pulang cepat. Tapi entah bagaimana, seiring pena menggores di atas kertas, pikiran-pikiran saya mengalir begitu saja dan sakit kepala itu sama sekali tidak terasa. Akhirnya, setelah menulis sebanyak tiga lembar halaman kertas folio, saya melihat kembali karya saya dan berpikir: “Hey, this is actually good enough for the blog!” Jadi begitulah cerita di balik pemuatan artikel hari ini. I’m not usually make a disclaimer before an article and this is getting too long, so let’s get on to it.
Pertanyaan kuis yang diajukan pada Rabu lalu cukup sederhana, namun cukup terbuka untuk mengundangku berpikir lebih dalam. Pertanyaannya kurang lebih adalah sbb:
“Jelaskan bagaimana paradigma (1) liberalisme; (2) realisme; dan (3) konstruktivisme memandang soal hak asasi manusia (HAM), kemudian jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing paradigma beserta contoh konkret.”
1. Liberalisme
Paradigma liberalisme memandang HAM sebagai sesuatu yang perlu diinstitusionalisasi dalam bentuk legal-formal. Dalam hal ini, liberalisme memandang bahwa pelanggaran HAM terjadi karena tidak adanya aturan yang secara spesifik memerintahkan aktor internasional untuk bertindak sesuai prinsip HAM. Perspektif ini kemudian melahirkan produk-produk, seperti hukum internasional, organisasi internasional, deklarasi dan segala teks yang bersifat materiil. Dengan keberadaan teks tersebut, liberalisme meyakini bahwa masing-masing aktor internasional akan memiliki panduan untuk membentuk perilaku yang menjunjung-tinggi nilai-nilai HAM.Kelebihan liberalisme adalah mampu mengajukan pandangan yang mudah dimengerti semua orang mengenai apa itu HAM dan mengapa hal tersebut menjadi penting. Hal ini menjadi mungkin melalui keberadaan teks hukum internasional yang bersifat materiil sehingga dapat dikonsumsi siapapun. Akan tetapi, kelemahan paradigma ini terletak pada asumsi bahwa negara dan aktor lainnya pasti akan mengikuti panduan yang tertuang dalam teks hukum internasional. Saya memandang bahwa hal ini akan sulit, jika bukan mustahil, karena hukum internasional merupakan sebuah paradox dimana mereka menyajikan norma hukum yang secara eksplisit harus dipatuhi (complied), namun norma tersebut tidak dapat diberlakukan (enforced). Paradoks ini terjadi karena tidak ada otoritas tunggal di tingkat internasional yang mampu memaksa seluruh aktor untuk mematuhi hukum tersebut. Dengan demikian, pelanggaran HAM tetap dapat terjadi meski sudah ada hukum internasional.
Sebagai contoh, Genosida Rwanda pada tahun 1993 merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM terbesar dalam sejarah modern dan hal tersebut berlangsung di bawah pengawasan PBB. United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) merupakan nama yang cukup catchy untuk misi PBB, namun ia juga merupakan abjek kegagalan bagi organisasi internasional terbesar di dunia ini. UNAMIR telah memulai misinya semenjak Oktober 1993 untuk mengawasi penerapan Perjanjian Damai Arusha. Secara singkat, UNAMIR telah ditugaskan secara spesifik oleh Dewan Keamanan PBB untuk memastikan agar tidak ada pecah konflik antara Suku Hutu dan Suku Tutsi. Namun pada kenyataannya, UNAMIR sama sekali tidak menyadari bahwa kekuasaan Hutu semakin kuat dari hari ke hari. Ketika pesawat yang ditumpangi Presiden Hutu ditembak jatuh, UNAMIR sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa untuk mencegah peristiwa tersebut bereskalasi menjadi kekejaman berdarah terbesar setelah Perang Dunia II. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana institusi internasional yang paling merepresentasikan nilai-nilai HAM sama sekali tidak berdaya untuk mencegah pelanggaran HAM yang terjadi di depan mata mereka.
2. Realisme
Paradigma realisme memandang HAM sebagai salah satu dari target yang harus dicapai sebagai bagian dari kepentingan nasional suatu negara. Bagi realisme, HAM merupakan sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh negara kuat yang mampu melindungi dirinya dari negara lain. Penjelasan yang diberikan oleh realisme terkait pertanyaan “Mengapa suatu negara gagal melindungi HAM penduduknya?” adalah karena negara tersebut terlalu lemah, baik dari segi militer, ekonomi, maupun relasi politik. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan oleh realisme terkait pemenuhan HAM adalah setiap negara harus menjadi kuat. Hanya negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar, disertai militer yang tangguh untuk melindunginya, yang dapat melindungi HAM. Jika suatu negara tidak memiliki kapasitas di kedua bidang tersebut, maka ia harus membangun relasi politik yang baik dengan negara kuat lainnya agar mereka bersedia melindungi.Kelebihan dari paradigma realisme adalah menyediakan solusi yang terdengar sangat realistis (sesuai namanya) untuk melindungi HAM. Walaupun orang-orang mungkin dapat menyatakan bahwa argumen realisme terlalu menggunakan common sense, namun tidak dapat dipungkiri bahwa solusi paling elegan dan simpel untuk memenuhi HAM adalah dengan menjadi kuat. Akan tetapi, kelemahan utama dari paradigma ini adalah ia menciptakan sebuah lingkungan dimana relasi antar negara berlangsung dengan logika zero-sum game. Bagaimanapun juga, istilah ‘kuat’ merupakan istilah relatif yang tidak dapat berdiri tanpa keberadaan pihak ‘lemah’ yang menjadi relatif dari si kuat. Dengan demikian, tidak semua negara dapat menjadi negara kuat. Akan selalu ada pihak lemah yang menjadi santapan si kuat yang tidak akan pernah mampu memenuhi HAM penduduknya. Ketika seluruh negara di dunia menerapkan paradigma realisme, maka dunia akan menjadi ajang survival of the fittest dimana yang kuat akan memakan yang lemah. Tentu dunia semacam itu sangat jauh dari cita-cita yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1945.
Kelemahan lain dari realisme adalah mengasumsikan bahwa negara merupakan satu-satunya aktor yang dapat melindungi HAM. Asumsi ini sangat menyesatkan setidaknya dalam dua level. PErtama, negara bukan satu-satunya aktor yang relevan dalam hubungan internasional. Aktor non-negara, seperti NGO internasional dan jejaring advokasi transnasional, memiliki peranan yang signifikan untuk perlindungan HAM. Kedua, negara memang dapat menjadi penjamin HAM, namun pada prakteknya mereka lebih sering menjadi pelanggar HAM. Agamben (2005) telah menjelaskan hal ini melalui teori Kondisi Pengecualian dimana ia menemukan bahwa negara berdaulat memiliki fitur untuk mengecualikan hak sebagian penduduknya yang ditetapkan sebagai homo sacer (manusia yang dapat dikorbankan). Hal ini dapat terlihat contohnya pada kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau komunitas Syiah atau simpatisan PKI, yang mendapati hak mereka sebagai manusia dilanggar oleh negara hanya karena logika kedaulatan yang absurd. Fitur inilah yang menurut saya membuat negara menjadi aktor yang tidak dapat diandalkan untuk melindungi HAM dan membuktikan bahwa asumsi realisme masih perlu dipertanyakan kembali.
3. Konstruktivisme
Paradigma konstruktivisme menekankan pentingnya ideational force sebagai aspek immaterial yang mempengaruhi perilaku negara. Bagi konstruktivisme, tidak ada satu hal pun di duni ini yang bersifat terberi (given). Entah namanya anarki, negara, ataupun HAM, semua itu adalah sesuatu yang tercipta berdasarkan kesepakatan sekelompok manusia di zaman tertentu yang kemudian dilestarikan melalui proses sosialisasi. Jika besok kita bangun di pagi hari dan semua orang sepakat bahwa HAM itu bullshit dan nasionalisme a la Nazi is the hot shit, maka realita yang akan tercipta adalah realita dimana kita menyapa sesama manusia dengan seruan “hail Hitler!” Oleh sebab itu, paradigma konstruktivisme percaya bahwa HAM hanya dapat dipenuhi jika semua orang sepakat bahwa ide mengenai HAM adalah ide yang terbaik. Tentu ketika kita membicarakan HAM, maka yang kita maksud adalah HAM sesuai dengan Deklarasi PBB pada tahun 1945. Berbagai budaya lokal di dunia memiliki konsepsi HAM masing-masing, sehingga paradigma konstruktivisme senantiasa menekankan pentingnya melakukan sosialisasi secara jelas agar setiap orang menerima dan mempercayai ide HAM yang kamu maksud. Jika kamu percaya bahwa ide HAM sesuai dengan anjuran PBB adalah ide yang terbaik, maka yang harus kamu lakukan adalah terus mempromosikan dan mensosialisasikannya agar semua orang bersedia untuk menyepakatinya.Kelebihan dari konstruktivisme adalah mampu mengajukan solusi yang jauh lebih efektif dibandingkan liberalisme. Jika liberalisme hanya berkutat pada penciptaan institusi formal yang dapat menjadi panduan seluruh aktor internasional, konstruktivisme justru melangkah lebih jauh ke ranah yang lebih intim dengan cara membuat seluruh aktor internasional meresapi nilai HAM sebagai bagian dari prinsip hidup mereka. Ketika seseorang sudah meyakini bahwa prinsip HAM versi PBB adalah yang benar, maka mereka tidak akan ragu-ragu untuk mengutuk diskriminasi kaum Wahabbi terhadap minoritas Islam di Indonesia, meskipun mereka sendiri adalah penganut Sunni dan meskipun tidak ada aturan yang secara eksplisit memerintahkan mereka untuk melakukan itu. Konstruktivisme mempengaruhi manusia di ranah yang paling intim, sehingga prinsip HAM bukan lagi menjadi kewajiban, melainkan sesuatu yang diyakini kebenarannya.
Akan tetapi, solusi yang ditawarkan konstruktivisme tidak akan pernah maksimal karena sosialisasi ide dan penanaman nilai bukanlah sesuatu yang eksklusif dimiliki oleh aktifis pembela HAM. Kelompok anti-HAM juga mampu melakukan hal tersebut, sehingga apa yang terjadi kemudian adalah kontestasi gagasan yang dapat merusak tatanan sosial. Pengepungan LBH Jakarta pada September lalu menujukkan wujud nyata dari kontestasi ide mengenai HAM versi PBB (yang menganggap simpatisan komunis sebagai korban pelanggar HAM) dan HAM versi Orde Baru (yang menganggap simpatisan komunis sebagai pelaku pelanggaran HAM itu sendiri). Di sinilah kelemahan konstruktivisme menjadi terlihat dimana paradigma ini tidak dapat menyatakan keberpihakkannya dalam situasi kontestasi ide. Bagaimanapun juga, konstruktivisme merupakan pendekatan yang masih terkungkung oleh logika positivistic yang mengharuskan sikap objektif (semu) dalam melihat fenomena sosial. Pada akhirnya, konstruktivisme sendiri tidak dapat benar-benar menjadi paradigma yang ideal dalam upaya pemenuhan HAM.

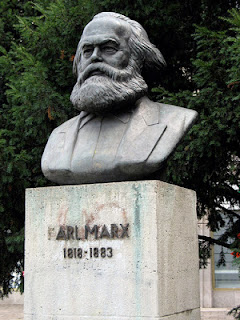

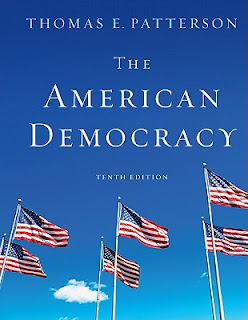

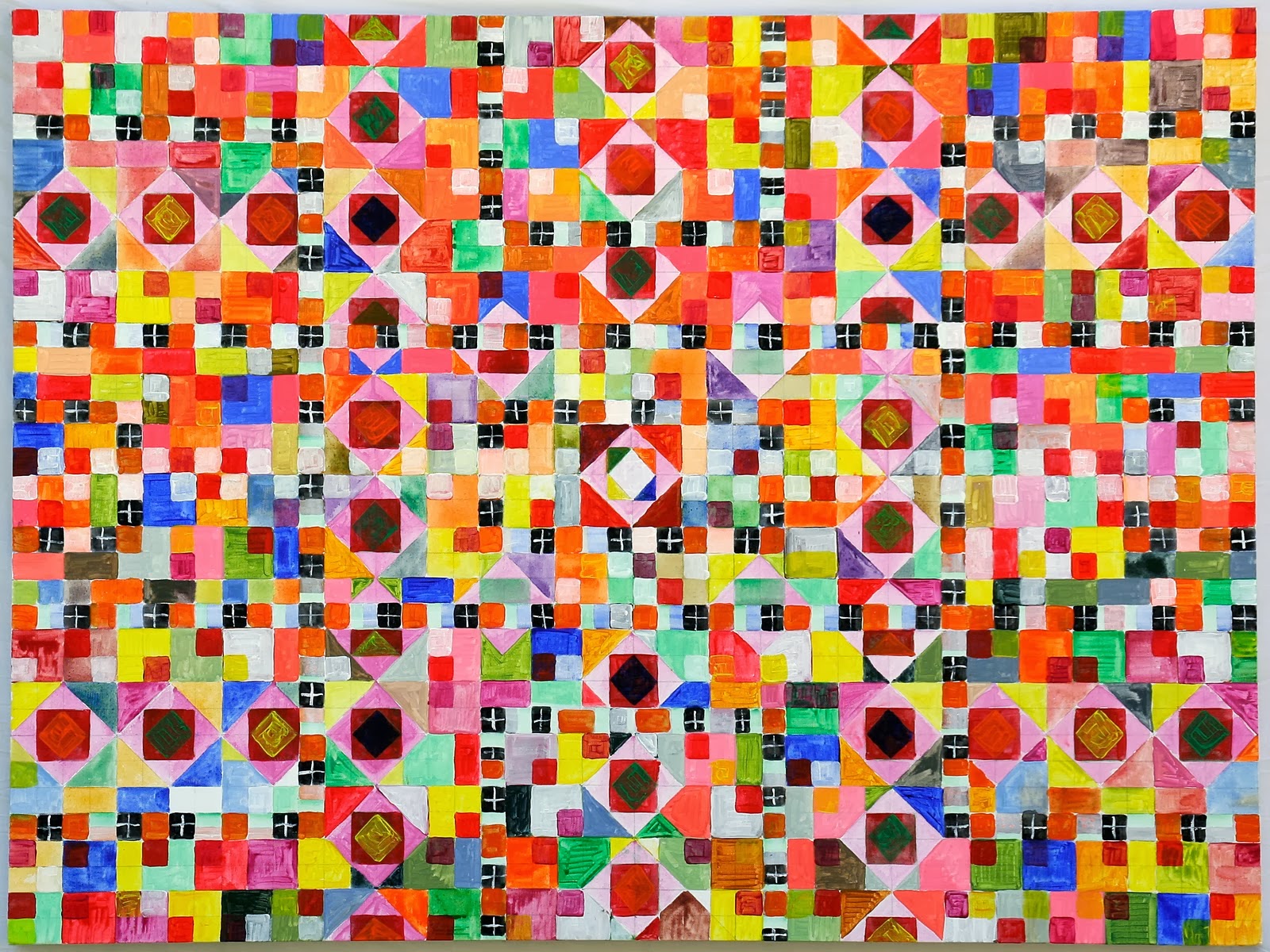
Comments
Post a Comment