Regionalisme Isu Lingkungan di Asia Tenggara (1977-2000)
Tulisan ini sebelumnya telah dipublikasikan dalam Andalas Journal Vol. 5 No. 1 (Mei 2016)
ASEAN adalah organisasi regional yang telah memiliki sejarah panjang dalam memfasilitasi proses regionalisme di Asia Tenggara. Berbagai dimensi kehidupan telah melewati proses integrasi berkat adanya regionalisme di Asia Tenggara, seperti politik, ekonomi, budaya dan lingkungan. Dimensi yang terakhir disebut, yakni dimensi lingkungan, merupakan topik bahasan utama dalam makalah ini.
Semenjak tahun 1970-an, kawasan Asia Tenggara telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kebanyakan akademisi yang mengkaji kawasan Asia Tenggara berargumen bahwa pergeseran motor ekonomi dari agrikultur ke industrialisasi merupakan penyebab utama dari pertumbuhan ekonomi yang pesat tersebut.[1]
Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang pesat memberikan kesempatan bagi warga Asia Tenggara untuk mencicipi kehidupan masyarakat kelas menengah ala Barat. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat di Asia Tenggara menyebabkan degradasi lingkungan yang amat parah. Penggundulan hutan, polusi saluran air, penurunan kualitas udara di perkotaan, mewujud sebagai konsekuensi dari degradasi lingkungan yang terjadi di Asia Tenggara.[2]
Pada satu titik, negara-negara Asia Tenggara menyadari bahwa persoalan lingkungan bukanlah sesuatu yang dapat dibatasi oleh teritorial negara. Ketika terjadi penggundulan hutan di Kalimantan yang mengakibatkan kebakaran hutan, asap kebakaran tersebut tidak hanya akan berdampak pada masyarakat di Kalimantan saja, tapi juga masyarakat di Sabah, masyarakat di Singapura, masyarakat di Bandar Sri Begawan, dan seluruh wilayah yang berdekatan dengan kalimantan.[3]
Pada satu titik, negara-negara Asia Tenggara menyadari bahwa persoalan lingkungan bukanlah sesuatu yang dapat dibatasi oleh teritorial negara. Ketika terjadi penggundulan hutan di Kalimantan yang mengakibatkan kebakaran hutan, asap kebakaran tersebut tidak hanya akan berdampak pada masyarakat di Kalimantan saja, tapi juga masyarakat di Sabah, masyarakat di Singapura, masyarakat di Bandar Sri Begawan, dan seluruh wilayah yang berdekatan dengan kalimantan.[3]
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan merupakan persoalan yang bersifat transnasional, sehingga dibutuhkan solusi yang bersifat transnasional pula. Namun, warisan sistem Westphalia yang menjustifikasi interaksi antarnegara berdasarkan kepentingan nasional menjadi penghalang bagi terciptanya solusi transnasional terkait isu lingkungan di Asia Tenggara.
Semenjak tahun 1977, Regionalisme merupakan jawaban yang diberikan ASEAN terhadap persoalan lingkungan yang terjadi di Asia Tenggara. Melalui regionalisme, ASEAN menawarkan sebuah perubahan secara gradual dan perlahan-lahan bagi kondisi hubungan internasional di Asia Tenggara.
Semenjak tahun 1977, Regionalisme merupakan jawaban yang diberikan ASEAN terhadap persoalan lingkungan yang terjadi di Asia Tenggara. Melalui regionalisme, ASEAN menawarkan sebuah perubahan secara gradual dan perlahan-lahan bagi kondisi hubungan internasional di Asia Tenggara.
Melalui regionalisme, ASEAN memvisualisasikan Asia Tenggara yang dapat mengesampingkan kepentingan nasionalnya masing-masing dan menjadikan isu lingkungan sebagai sebuah kepentingan transnasional yang harus diselesaikan bersama. Solusi ini kemudian menimbulkan pertanyaan. Bagaimanakah proses regionalisme isu lingkungan yang telah terjadi di Asia Tenggara? Sudah sejauh manakah proses regionalisme itu terjadi?
Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan di atas, makalah ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Pada bagian pertama, akan dijelaskan kerangka analisis yang digunakan makalah ini untuk menjelaskan proses regionalisme di Asia Tenggara. Secara singkat, makalah ini akan menerapkan Teori Regionalisme Baru yang dikembangkan oleh Bjorn Hettne.
Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan di atas, makalah ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Pada bagian pertama, akan dijelaskan kerangka analisis yang digunakan makalah ini untuk menjelaskan proses regionalisme di Asia Tenggara. Secara singkat, makalah ini akan menerapkan Teori Regionalisme Baru yang dikembangkan oleh Bjorn Hettne.
Berdasarkan teori tersebut, regionalisme berkembang melalui lima fase. Perasaan kekawasanan (regionness) merupakan kunci bagi perkembangan fase-fase tersebut. Pada bagian kedua, akan dijelaskan kronologi kerjasama isu lingkungan di Asia Tenggara dari tahun 1977-2000. Pada bagian ketiga, makalah ini akan melakukan analisis terhadap objek analisa yang telah dijelaskan pada bagian kedua melalui teori yang telah dijelaskan pada bagian pertama.
Analisis tersebut akan menyimpulkan bahwa sampai tahun 2000, regionalisme di Asia Tenggara telah berjalan dan telah mencapai fase ketiga serta sedang berusaha untuk mencapai fase keempat.
Kawasan adalah sebuah entitas geografis yang berkembang melalui adanya integrasi yang berlandaskan pada kepentingan bersama. Regionalisme adalah sebuah proses politik yang mengarah pada peningkatan integrasi dari kawasan. Makalah ini akan menerapkan Teori Regionalisme Baru yang dikembangkan oleh Bjorn Hettne.
Teori
Regionalisme Baru
Hettne menjelaskan regionalisme sebagai “Sebuah proses dimana entitas geografis bertransformasi dari sekedar objek pasif menjadi subjek aktif yang mampu untuk mengartikulasikan kepentingan transnasional dari kawasan itu sendiri.”[4] Proses tersebut berlangsung dalam lima fase.[5]
adanya sekumpulan orang yang tinggal berdekatan secara geografis, memiliki suatu sumber daya alam yang dibagi bersama, dan memiliki kesamaan nilai-nilai budaya yang terbentuk akibat sejarah. Kondisi ruang yang demikian akan memicu terjadinya interaksi di antara orang-orang yang tinggal di dalam ruang tersebut, sehingga proses regionalisme akan mengarah pada fase kedua, yakni regional
complex.
3. Regional Society. Pada fase ketiga dari regionalisme, akan terjadi formalisasi kawasan. Interaksi yang tercipta di antara negara-negara mulai mengarah kepada interaksi yang berdasarkan pada aturan yang disepakati bersama. Sebuah organisasi dapat tercipta dalam fase ini untuk memfasilitasi pembuatan aturan bersama tersebut. Dengan adanya kawasan yang semakin terorganisir, maka rasa saling percaya di antara aktor-aktor yang ada menjadi memungkinkan. Sehingga interaksi di antara mereka dapat diangkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi untuk mengarah pada satu bentuk komunitas.
4. Regional Community. Pada fase keempat dari regionalisme, akan tercipta homogenisasi kawasan. Identitas bersama akan mulai dibangun pada fase ini seiring meningkatnya rasa saling percaya di antara negara-negara yang ada di dalam kawasan. Perbatasan antarnegara tidak lagi menjadi sekat pemisah, namun menjadi penghubung yang semakin menyatukan kepentingan dari tiap-tiap negara. Sebaliknya, sekat pemisah justru akan semakin terasa dalam membedakan negara yang berada di dalam kawasan dengan yang di luar kawasan. Hal ini tidak lain tercipta karena adanya pembentukan identitas dari kawasan tersebut.
5. Regional State. Pada fase terakhir dari regionalisme, interaksi, organisasi, dan homogenisasi, yang telah terjadi pada fase sebelumnya, akan membungkus kawasan ke dalam satu bentuk negara. Namun, regional state (negara kawasan) harus dibedakan dari nation state (negara bangsa) yang logika politiknya merupakan standarisasi dari satu model etnis tertentu. Negara kawasan yang tercipta dari gabungan beberapa negara bangsa harus dapat mengkompromikan perbedaan kebudayaan dari tiap negara dalam sebuah kebudayaan plural.
Berdasarkan kelima fase tersebut, dapat diidentifikasi bahwa faktor utama yang dapat menyebabkan perpindahan fase regionalisme adalah intensitas interaksi transnasional. Dalam bahasa Bjorn Hettne, intensitas interaksi transnasional akan menciptakan sebuah perasaan yang disebut dengan kekawasanan (regionness). Regionness dapat dipahami dengan menganalogikan kenegaraan (stateness) atau kebangsaan (nationness). Semakin tinggi tingkat regionness, semakin tinggi pula fase regionalisme dari sebuah kawasan.[6]
Pada fase pertama, regionness masih belum tercipta, namun syarat-syarat yang memungkinkan terciptanya regionness sudah terbentuk. Pada fase kedua, regionness sudah mulai terbentuk, namun masih dilandasi oleh kepentingan nasional. Pada fase ketiga, regionness sudah mencapai tingkat menengah, dibuktikan dengan adanya seperangkat aturan formal yang melandasi interaksi kawasan. Pada fase keempat, regionness sudah mencapai tingkat tinggi, dibuktikan dengan adanya identitas bersama yang membedakan kawasan tersebut dengan kawasan lainnya. Pada fase terakhir, regionness telah mencapai tingkat tertingginya, dibuktikan dengan adanya sistem negara yang menjadi dasar bagi interaksi kawasan.[7]
Sejarah panjang kerjasama isu lingkungan di Asia Tenggara dimulai dengan kunjungan United Nations Environment Program (UNEP) pada tahun 1977 dengan tujuan mengajak negara-negara ASEAN untuk mendukung program penyelamatan lingkungan yang dilaksanakan oleh PBB. Kunjungan tersebut membuahkan draf program lima tahunan yang nantinya akan dikenal dengan nama ASEP.[10] Setahun kemudian, draft ASEP dibawa ke dalam pertemuan pertama dari ASEAN Expert Group on the Environment (AEGE)[11].
Kronologi
Kerjasama Isu Lingkungan Asia Tenggara
Asia Tenggara adalah sebuah wilayah yang memiliki sejarah paling panjang terkait kerjasama isu lingkungan dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di Asia dan Pasifik. Hal ini terjadi berkat dibentuknya organisasi regional bernama ASEAN di tahun 1967. ASEAN yang pada waktu itu masih beranggotakan lima negara Asia Tenggara[8] menginisiasi adanya kerjasama lingkungan di antara anggota-anggotanya melalui pembentukan ASEAN Subregional Environmental Program (ASEP) pada tahun 1977. Semenjak itu, berbagai program, rencana, deklarasi, dan resolusi terus menerus diadopsi atau diimplementasikan. Struktur organisasi untuk kerjasama isu lingkungan pun perlahan-lahan berkembang.[9]
Bagian ini akan menjelaskan kronologi kerjasama isu lingkungan di Asia Tenggara semenjak tahun 1977 sampai tahun 2000. Beberapa momen penting yang perlu diperhatikan dalam kerjasama isu lingkungan di Asia Tenggara adalah: Pembentukan ASEP tahun 1977, pertemuan pertama ASEAN Experts Group on the Environment (AEGE) pada tahun 1978, pertemuan pertama ASEAN Ministerial Meeting on Environment (AMME) pada tahun 1981, pengadopsian ASEAN Agreement on Conservation of Nature and Natural Resources (ACNNR) pada tahun 1985, Pertemuan pertama ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN) pada tahun 1989, pembentukan ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution (ACPTP) pada tahun 1994, dan pembentukan ASEAN Vision 2020 pada tahun 1997.
Tabel 1
Timeline Kerjasama Isu Lingkungan di Asia Tenggara
tahun 1977-2000
Tahun
|
Event Utama
|
Output
|
|
1977
|
Kunjungan UNEP terhadap ASEAN
|
Pembentukan draft ASEP
|
|
1978
|
Pertemuan pertama AEGE
|
Fiksasi program ASEP
|
|
1981
|
Pertemuan pertama AMME
|
Manila Declaration on ASEAN Environment
|
|
1984
|
Pertemuan AEGE ke-7
|
Review terhadap ASEP
|
|
1985
|
ASEAN Agreement on Conservation of Nature and
Natural Resources
|
Pembentukan prinsip anti-transboundary
environmental impacts
|
|
1989
|
Pertemuan pertama ASOEN
|
Struktur kerjasama Isu Lingkungan ASEAN
|
|
1994
|
Pertemuan informal AMME
|
Pembentukan ACPTP
|
|
1997
|
ASEAN Summit
|
ASEAN Vision 2020
|
|
2000
|
Pertemuan AMME ke-8
|
Kota Kinabalu Resolution on the Environment
|
Para peserta pertemuan tersebut membahas area-area yang harus menjadi prioritas dari ASEP dan mulai melakukan serangkaian aktivitas, seperti mengembangkan dan menguji metodologi baru untuk mengatasi persoalan isu lingkungan, membuat daftar spesies yang terancam punah, dan melaksanakan survey terhadap kapabilitas pengawasan kualitas air/udara dari masing-masing pemerintah negara anggota ASEAN.
Enam area prioritas ASEP ditentukan melalui pertemuan AEGE yang pertama, yaitu: (1) Manajemen Lingkungan termasuk Penaksiran Dampak Lingkungan (EIA); (2) Konservasi Alam; (3) Industri dan Lingkungan; (4) Pendidikan dan Pelatihan terkait Lingkungan; (5) Informasi dan Data terkait Lingkungan; (6) Lingkungan Maritim.[12]
Pada tahun 1981, pertemuan pertama AMME[13] digelar di Manila, Filipina, dan menghasilkan Manila Declaration on ASEAN Environment. Isi dari deklarasi tersebut dirangkum oleh Weatherbee sebagai berikut: “ASEAN memiliki kepentingan bersama dalam menghadapi isu lingkungan dikarenakan adanya kebutuhan untuk memastikan perlindungan terhadap lingkungan ASEAN dan ketersediaan sumber daya alamnya agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan di negara-negara ASEAN.”[14] Selain deklarasi, pertemuan pertama AMME juga berhasil menyetujui ASEP, yang selanjutnya disebut dengan ASEP-I, sekaligus mendukung pengembangan program tersebut ke depannya.
Tiga tahun kemudian, diadakan pertemuan AEGE ke-7 yang menyetujui pengimplementasian ASEP-II yang akan melanjutkan usaha-usaha yang telah dilakukan ASEP-I dari tahun 1978-1983. ASEP-I dianggap telah berhasil menciptakan semangat kerjasama isu lingkungan di antara negara-negara anggota ASEAN. Untuk melanjutkan usahanya, maka ASEP II diarahkan untuk lebih berorientasi terhadap aksi dan menekankan pada proyek-proyek demonstrasi (Lihat Tabel 2).
Pada tahun 1981, pertemuan pertama AMME[13] digelar di Manila, Filipina, dan menghasilkan Manila Declaration on ASEAN Environment. Isi dari deklarasi tersebut dirangkum oleh Weatherbee sebagai berikut: “ASEAN memiliki kepentingan bersama dalam menghadapi isu lingkungan dikarenakan adanya kebutuhan untuk memastikan perlindungan terhadap lingkungan ASEAN dan ketersediaan sumber daya alamnya agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan di negara-negara ASEAN.”[14] Selain deklarasi, pertemuan pertama AMME juga berhasil menyetujui ASEP, yang selanjutnya disebut dengan ASEP-I, sekaligus mendukung pengembangan program tersebut ke depannya.
Tiga tahun kemudian, diadakan pertemuan AEGE ke-7 yang menyetujui pengimplementasian ASEP-II yang akan melanjutkan usaha-usaha yang telah dilakukan ASEP-I dari tahun 1978-1983. ASEP-I dianggap telah berhasil menciptakan semangat kerjasama isu lingkungan di antara negara-negara anggota ASEAN. Untuk melanjutkan usahanya, maka ASEP II diarahkan untuk lebih berorientasi terhadap aksi dan menekankan pada proyek-proyek demonstrasi (Lihat Tabel 2).
Tabel 2
Aktivitas Utama di bawah ASEP-I dan ASEP-II
Area Prioritas
|
Aktivitas Utama di Bawah ASEP-I
|
Aktivitas Utama di Bawah ASEP-II
|
Manajemen Lingkungan
termasuk Penanganan Kerusakan Lingkungan (EIA)
|
Berhasil memastikan
keinginan negara-negara ASEAN dalam menggunakan EIA sebagai alat manajemen
|
· Pengembangan metodologi perencanaan lingkungan
· pengembangan panduan EIA dan aplikasinya dalam
proyek industri
· pengembangan jaringan regional yang terdiri
dari institusi terkait
|
Konservasi Alam
|
Membuat Action Plan, diadopsi AEGE tahun 1981
|
Implementasi Action Plan, terutama:
· Pengembangan dan promosi jaringan regional
· promosi program pelatihan saintifik dan
sistematik
· implementasi instrumen regional dalam
meregulasi perdagangan internasional spesies flora dan fauna yang terancam
punah
|
Industri dan
Lingkungan
|
Menyadari bahwa manajemen
kualitas lingkungan perkotaan di Singapura dapat dijadikan model untuk negara
lainMembuat rencana aksi yang disiapkan UNESCO dan diadopsi AEGE tahun 1983
|
· Transfer teknologi organo-industrial
pollution control,
· Peningkatan kapabilitas ASEAN dalam pengendalian
polusi udara dan pengawasan,
· Persiapan panduan kebijakan terkait
transportasi,
· perawatan pengumpulan dan pembuangan substansi
berbahaya
|
Pendidikan dan
Pelatihan terkait Lingkungan
|
Membuat Action Plan yang disiapkan UNESCO dan
diadopsi AEGE pada tahun 1983
|
Mempromosikan
pendidikan lingkungan melalui:
· Pengembangan kurikulum untuk pendidikan formal
dan nonformal,
· Pelatihan terkait pengendalian
polusi/limbah/konservasi alam
|
Informasi dan Data
terkait Lingkungan
|
Mengembangkan profil
situasi lingkungan tiap negara, mempublikasikan ASEAN newsletter,
mempromosikan Hari Lingkungan Dunia (WED)
|
· workshop untuk jurnalis,
· workshop untuk LSM,
· ASEAN newsletter,
· kolaborasi regional terkait WED,
· pengumpulan data dan informasi lingkungan
|
Lingkungan Maritim
|
Membuat East Asia Sea
(EAS) Action Plan yang disiapkan UNEP dan di-review oleh AEGE di tahun
1980
|
ASEAN Standing
Committee ke-6 di tahun 1981 memutuskan bahwa EAS Action Plan adalah bagian
dari UNEP, sehingga AEGE hanya perlu untuk mengawasi berlangsungnya program
tersebut
|
|
Sumber: Institute for Global Environment Strategies
|
ACNNR juga mengakui pentingnya mengurangi polusi dan membuat prinsip untuk menghindari aktivitas yang memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan lintas negara (Transboundary Environmental Impacts).[17] Dengan kata lain, ACNNR telah berhasil membuat prinsip-prinsip yang berguna untuk meminimalisir dampak Transboundary Environmental Impacts. Ditambah lagi, ACNNR untuk pertama kalinya menyediakan sebuah peraturan formal yang bersifat mengikat secara hukum bagi negara-negara yang menyepakatinya.[18] Sayangnya, ACNNR tidak pernah dapat dijalankan karena tidak mendapatkan ratifikasi yang cukup dari keenam negara anggota ASEAN.[19]
Lima tahun kemudian, terjadilah salah satu momen penting dalam kerjasama lingkungan di Asia Tenggara. Bertepatan dengan dibentuknya ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN), menggantikan AEGE, struktur institusi awal dari kerjasama lingkungan ASEAN pun ikut dibentuk (Lihat Tabel 3). Aktor utamanya adalah ASOEN beserta Working Group di bawahnya, AMME, dan Sekretariat ASEAN.[20]
ASOEN, yang beranggotakan kepala departemen lingkungan masing-masing negara ASEAN, akan bertemu setiap tahun sekali dan bertanggung jawab untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengawasi program/aktivitas regional terkait isu lingkungan. ASOEN dibantu oleh empat Working Group yang akan melaporkan hasil kerjanya kepada ASOEN secara langsung.[21] AMME masih bekerja dengan pola yang sama semenjak tahun 1981, namun dengan posisi yang lebih jelas di atas ASOEN.
Lima tahun kemudian, terjadilah salah satu momen penting dalam kerjasama lingkungan di Asia Tenggara. Bertepatan dengan dibentuknya ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN), menggantikan AEGE, struktur institusi awal dari kerjasama lingkungan ASEAN pun ikut dibentuk (Lihat Tabel 3). Aktor utamanya adalah ASOEN beserta Working Group di bawahnya, AMME, dan Sekretariat ASEAN.[20]
ASOEN, yang beranggotakan kepala departemen lingkungan masing-masing negara ASEAN, akan bertemu setiap tahun sekali dan bertanggung jawab untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengawasi program/aktivitas regional terkait isu lingkungan. ASOEN dibantu oleh empat Working Group yang akan melaporkan hasil kerjanya kepada ASOEN secara langsung.[21] AMME masih bekerja dengan pola yang sama semenjak tahun 1981, namun dengan posisi yang lebih jelas di atas ASOEN.
Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai resource base yang menyediakan informasi untuk membantu kinerja seluruh badan di dalam struktur ini. Sekretariat ASEAN juga berfungsi untuk mengkoordinir badan-badan di dalam struktur dengan mitra kerja dari luar ASEAN. Sementara itu, ASEAN Summit yang posisinya paling tinggi di dalam struktur hanya berfungsi sebatas memberikan visi besar bagi kerjasama lingkungan yang diinisiasi badan-badan di bawahnya.[22]
Pada tahun 1991, kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan menyebar ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei mengalami kerugian ekonomi dan masalah kesehatan yang parah akibat peristiwa tersebut. Begitu pula dengan Thailand dan Filipina, walaupun kerugiannya tidak separah keempat negara lainnya. ASEAN Summit yang merupakan komando tertinggi kerjasama lingkungan ASEAN mengidentifikasi persoalan polusi udara sebagai masalah bersama ASEAN.
Pada tahun 1991, kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan menyebar ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei mengalami kerugian ekonomi dan masalah kesehatan yang parah akibat peristiwa tersebut. Begitu pula dengan Thailand dan Filipina, walaupun kerugiannya tidak separah keempat negara lainnya. ASEAN Summit yang merupakan komando tertinggi kerjasama lingkungan ASEAN mengidentifikasi persoalan polusi udara sebagai masalah bersama ASEAN.
Hasil dari ASEAN Summit kemudian dibawa ke pertemuan informal AMME tahun 1994 dan menghasilkan sebuah rencana kerja baru dalam kerjasama lingkungan ASEAN, yaitu ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution (ACPTP). ACPTP terdiri dari tiga area prioritas, yaitu: (1) polusi atmosfer lintas batas; (2) polusi zat buangan kapal laut lintas batas; (3) pergerakan limbah lintas batas. Selain itu, ACPTP juga dilengkapi dengan kerangka kerja yang jelas, seperti tujuan, strategi, pemilihan institusi yang terkait, sampai dengan pendataan ahli-ahli dan bantuan finansial yang memungkinkan untuk mengimplementasikan ACPTP. [23]
Pada tahun 1997, dalam ASEAN Summit di Kuala Lumpur, Malaysia, dibentuklah ASEAN Vision 2020 yang menggambarkan mimpi para pemimpin ASEAN akan masa depan kawasan Asia Tenggara. Terkait isu lingkungan, terdapat tiga mimpi yang dituliskan oleh para pemimpin ASEAN dalam ASEAN Vision 2020[24]:
Untuk mengimplementasikan mimpi mulia ASEAN Vision 2020, dibentuklah Hanoi Plan on Action (HNPA) pada tahun 1998, yang menetapkan seperangkat aturan untuk melindungi lingkungan Asia Tenggara. Belum cukup dengan HNPA, ASEAN juga membentuk Strategic Plan of Action on Environment (SPAE) pada tahun 1999.
Asia Tenggara sebelum tahun 1977 telah memenuhi kondisi yang dibutuhkan agar tercipta regionness dalam isu lingkungan. Wilayah Asia Tenggara terdiri dari sepuluh negara yang letak geografisnya berdekatan. Kesepuluh negara tersebut memiliki sumber daya alam yang mau tidak mau harus dibagi dengan sesamanya, seperti Sungai Mekong di daratan Indochina dan udara yang pergerakannya tidak dapat dibatasi oleh garis imajiner teritori. Lebih lagi, seluruh negara di Asia Tenggara, kecuali Laos, berbatasan dengan laut, sehingga segala sumber daya alam yang ada di laut akan terbagi-bagi di antara negara-negara Asia Tenggara.
Keberadaan sumber daya alam yang dibagi bersama jelas akan memicu terjadinya interaksi di antara negara-negara Asia Tenggara, baik interaksi yang berupa kerjasama maupun yang berupa konflik. Fakta menunjukkan bahwa persoalan lingkungan yang terjadi di Asia Tenggara hari ini memang mencakup sumber daya alam yang dibagi-bagi tersebut, seperti permasalahan limbah Sungai Mekong, Polusi udara yang diakibatkan kebakaran hutan, dan polusi gas buangan laut.[26] Dengan ditemukannya kondisi-kondisi yang memungkinkan terciptanya perasaan regionness dalam isu lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah regional area terkait isu lingkungan di Asia Tenggara telah tercipta sebelum tahun 1977.
Fase kedua regionalisme isu lingkungan di Asia Tenggara berlangsung dari tahun 1977-1989. Tahun 1977 menjadi titik awal dari fase kedua dikarenakan pada tahun tersebut UNEP mengunjungi ASEAN dan memicu terjadinya interaksi isu lingkungan untuk pertama kalinya di Asia Tenggara. Semenjak itu, ASEAN bertanggung jawab memfasilitasi interaksi di antara negara-negara Asia Tenggara terkait isu lingkungan melalui pertemuan-pertemuan rutin yang bersifat informal, seperti AEGE dan AMME. Fakta ini menunjukkan bahwa intensitas interaksi terkait isu lingkungan mulai meningkat semenjak tahun 1977.
Beberapa output dari interaksi yang terjadi pada tahun 1977-1989 mengindikasikan bahwa perasaan regionness terkait isu lingkungan di Asia Tenggara sudah tercipta. Regionness terkait isu lingkungan terlihat terutama dalam deklarasi-deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan AMME setiap tiga tahun sekali yang mana merupakan dokumen tertulis yang menyatakan kesiapan negara-negara ASEAN untuk menjadikan isu-isu lingkungan sebagai kepentingan kawasan. Program-program seperti ASEP-I dan ASEP-II yang diimplementasikan bersama-sama oleh seluruh negara ASEAN semakin menguatkan argumen bahwa perasaan regionness terkait isu lingkungan telah tercipta pada tahun 1977-1989.
Namun, perasaan regionness terkait isu lingkungan di Asia Tenggara pada tahun 1977-1989 masih pada tingkatan rendah. Analisa terhadap deklarasi dan program yang dibuat dalam kurun waktu tersebut menunjukkan bahwa mereka masih bersifat informal, tidak ada satu pun yang mengikat secara hukum. Salah satu kalimat dalam Manila Declaration on ASEAN Environment menyebutkan bahwa: perhatian terhadap lingkungan harus diikutsertakan dalam kebijakan pembangunan negara-negara anggota, ‘sejauh itu dapat dipraktekkan’. Kata-kata ‘sejauh itu dapat dipraktekkan’ terus diulang-ulang dalam pernyataan lainnya yang terkait konteks sustainable development dan konservasi aset lingkungan.[27]
Fase ketiga dari regionalisme isu lingkungan di Asia Tenggara berlangsung semenjak tahun 1989. Tahun tersebut menjadi titik awal dari fase ketiga karena di tahun tersebut untuk pertama kalinya dibuat struktur institusi yang jelas terkait kerjasama lingkungan di Asia Tenggara dan bersifat mengikat setiap negara anggota ASEAN dengam memberikan mereka tugas-tugas yang spesifik.
Analisis empirik terhadap kronologi kerjasama lingkungan Asia Tenggara dari tahun 1977-2000 masih belum menemukan elemen dari fase keempat regionalisme. Permasalahannya adalah karena belum ditemukan kasus yang menunjukkan bagaimana masyarakat Asia Tenggara telah memiliki satu identitas khusus terkait isu lingkungan yang membedakannya dengan kawasan lain.
Pada tahun 1997, dalam ASEAN Summit di Kuala Lumpur, Malaysia, dibentuklah ASEAN Vision 2020 yang menggambarkan mimpi para pemimpin ASEAN akan masa depan kawasan Asia Tenggara. Terkait isu lingkungan, terdapat tiga mimpi yang dituliskan oleh para pemimpin ASEAN dalam ASEAN Vision 2020[24]:
- Menciptakan atmosfer dagang ASEAN yang memenuhi kebutuhan lingkungan
- Menciptakan ASEAN yang bersih dan hijau berikut sebuah mekanisme untuk pembangunan berkesinambungan yang dapat memastikan perlindungan lingkungan kawasan, kesinambungan sumber daya alamnya, dan kualitas hidup yang tinggi bagi penduduknya
- Menciptakan Asia Tenggara yang memiliki seperangkat peraturan dan langkah-langkahkerjasama untuk mengatasi permasalahan yang hanya dapat ditemui dalam skala regional, seperti polusi dan degradasi lingkungan
Tabel 3
Struktur Kerjasama Isu Lingkungan ASEAN
Kedua program tersebut sama-sama ditujukan untuk meningkatkan standar perlindungan terhadap lingkungan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengikutsertakan proses formal untuk mengkodifikasi perjanjian perlindungan lingkungan. Pendekatan baru ini terlihat jelas dalam pertemuan AMME ke-8 di Kota Kinabalu dimana negara-negara anggota ASEAN melakukan proses negosiasi secara formal terkait isu polusi udara lintas batas.[25]
Dengan menggunakan Teori Regionalisme Baru, makalah ini berargumen bahwa regionalisme isu lingkungan di Asia Tenggara sampai tahun 2000 telah mencapai fase ketiga dari regionalisme dan sedang berusaha untuk menuju fase keempat.
Analisis Proses Regionalisme
Fase pertama dari regionalisme isu lingkungan di Asia Tenggara berlangsung sebelum tahun 1977. Fase kedua berlangsung dari tahun 1977-1989. Fase ketiga berlangsung semenjak tahun 1989. Usaha-usaha untuk mencapai fase keempat mulai terlihat semenjak tahun 1997. Secara detail, akan dijelaskan di bawah.
Fase pertama.
Asia Tenggara sebelum tahun 1977 telah memenuhi kondisi yang dibutuhkan agar tercipta regionness dalam isu lingkungan. Wilayah Asia Tenggara terdiri dari sepuluh negara yang letak geografisnya berdekatan. Kesepuluh negara tersebut memiliki sumber daya alam yang mau tidak mau harus dibagi dengan sesamanya, seperti Sungai Mekong di daratan Indochina dan udara yang pergerakannya tidak dapat dibatasi oleh garis imajiner teritori. Lebih lagi, seluruh negara di Asia Tenggara, kecuali Laos, berbatasan dengan laut, sehingga segala sumber daya alam yang ada di laut akan terbagi-bagi di antara negara-negara Asia Tenggara.
Keberadaan sumber daya alam yang dibagi bersama jelas akan memicu terjadinya interaksi di antara negara-negara Asia Tenggara, baik interaksi yang berupa kerjasama maupun yang berupa konflik. Fakta menunjukkan bahwa persoalan lingkungan yang terjadi di Asia Tenggara hari ini memang mencakup sumber daya alam yang dibagi-bagi tersebut, seperti permasalahan limbah Sungai Mekong, Polusi udara yang diakibatkan kebakaran hutan, dan polusi gas buangan laut.[26] Dengan ditemukannya kondisi-kondisi yang memungkinkan terciptanya perasaan regionness dalam isu lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah regional area terkait isu lingkungan di Asia Tenggara telah tercipta sebelum tahun 1977.
Fase kedua
Fase kedua regionalisme isu lingkungan di Asia Tenggara berlangsung dari tahun 1977-1989. Tahun 1977 menjadi titik awal dari fase kedua dikarenakan pada tahun tersebut UNEP mengunjungi ASEAN dan memicu terjadinya interaksi isu lingkungan untuk pertama kalinya di Asia Tenggara. Semenjak itu, ASEAN bertanggung jawab memfasilitasi interaksi di antara negara-negara Asia Tenggara terkait isu lingkungan melalui pertemuan-pertemuan rutin yang bersifat informal, seperti AEGE dan AMME. Fakta ini menunjukkan bahwa intensitas interaksi terkait isu lingkungan mulai meningkat semenjak tahun 1977.
Beberapa output dari interaksi yang terjadi pada tahun 1977-1989 mengindikasikan bahwa perasaan regionness terkait isu lingkungan di Asia Tenggara sudah tercipta. Regionness terkait isu lingkungan terlihat terutama dalam deklarasi-deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan AMME setiap tiga tahun sekali yang mana merupakan dokumen tertulis yang menyatakan kesiapan negara-negara ASEAN untuk menjadikan isu-isu lingkungan sebagai kepentingan kawasan. Program-program seperti ASEP-I dan ASEP-II yang diimplementasikan bersama-sama oleh seluruh negara ASEAN semakin menguatkan argumen bahwa perasaan regionness terkait isu lingkungan telah tercipta pada tahun 1977-1989.
Namun, perasaan regionness terkait isu lingkungan di Asia Tenggara pada tahun 1977-1989 masih pada tingkatan rendah. Analisa terhadap deklarasi dan program yang dibuat dalam kurun waktu tersebut menunjukkan bahwa mereka masih bersifat informal, tidak ada satu pun yang mengikat secara hukum. Salah satu kalimat dalam Manila Declaration on ASEAN Environment menyebutkan bahwa: perhatian terhadap lingkungan harus diikutsertakan dalam kebijakan pembangunan negara-negara anggota, ‘sejauh itu dapat dipraktekkan’. Kata-kata ‘sejauh itu dapat dipraktekkan’ terus diulang-ulang dalam pernyataan lainnya yang terkait konteks sustainable development dan konservasi aset lingkungan.[27]
Fakta ini menunjukkan bahwa deklarasi yang menyatakan kesiapan bagi negara-negara ASEAN terkait isu lingkungan masih memberikan kelonggaran bagi negara yang belum siap. Kalaupun ada perjanjian yang mengikat secara hukum, seperti ACCNR yang diadopsi pada tahun 1985, maka perjanjian tersebut tidak dapat bekerja karena kekurangan ratifikasi. Studi yang dilakukan oleh Lorraine Elliot menunjukkan bahwa kerjasama lingkungan di Asia Tenggara pada tahun 1977-1989 memang masih didasari pada kesukarelaan. Hal ini terkait dengan adanya norma-norma noninterferensi yang menekankan pada keutamaan hukum nasional, prioritas pembuatan keputusan di tingkat nasional, dan implementasi tingkat nasional.[28]
Selain itu, kerjasama isu lingkungan yang terjadi dalam kurun waktu 1977-1989 masih didasari oleh kepentingan nasional dan keuntungan relatif. Isu lingkungan, pada masa tersebut merupakan salah satu isu yang cukup seksi baik di tingkat internasional maupun nasional. Di tingkat internasional, isu lingkungan telah menjadi perhatian utama PBB berkat adanya Deklarasi Stockholm pada tahun 1972.[29] Di tingkat nasional, perhatian terhadap isu lingkungan merupakan permintaan utama dari komunitas-komunitas miskin yang termarjinalisasi akibat kerusakan lingkungan.[30]
Selain itu, kerjasama isu lingkungan yang terjadi dalam kurun waktu 1977-1989 masih didasari oleh kepentingan nasional dan keuntungan relatif. Isu lingkungan, pada masa tersebut merupakan salah satu isu yang cukup seksi baik di tingkat internasional maupun nasional. Di tingkat internasional, isu lingkungan telah menjadi perhatian utama PBB berkat adanya Deklarasi Stockholm pada tahun 1972.[29] Di tingkat nasional, perhatian terhadap isu lingkungan merupakan permintaan utama dari komunitas-komunitas miskin yang termarjinalisasi akibat kerusakan lingkungan.[30]
Dengan kata lain, hanya dengan menyetujui deklarasi atau program terkait isu lingkungan, negara-negara ASEAN telah mampu meningkatkan citranya di dunia internasional sekaligus menarik dukungan dari penduduk minoritasnya. Peningkatan citra di dunia internasional dan dukungan dari seluruh penduduknya tentu merupakan kepentingan nasional bagi negara mana pun di dunia. Fakta bahwa deklarasi dan program yang disetujui pada kurun waktu 1977-1989 masih memberikan kelonggaran bagi negara-negara ASEAN untuk tidak menjalankannya menguatkan argumen bahwa kepentingan nasional masih menjadi dasar bagi kerjasama lingkungan pada tahun 1977-1989.
Indikasi bahwa kerjasama lingkungan di Asia Tenggara pada tahun 1977-1989 masih didasari oleh keuntungan relatif terlihat terutama dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui ASEP-I dan ASEP-II. Jika melihat Tabel 2 pada bagian Kronologi Kerjasama Lingkungan Asia Tenggara, maka kita akan menemukan bahwa ASEP lebih berfokus pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya negara-negara ASEAN (Cont: pengembangan jaringan regional ASEAN untuk menghadapi isu lingkungan, Transfer teknologi organo-industrial pollution control, berbagai jenis pelatihan). Tidak ada satu pun kegiatan ASEP-I dan ASEP-II yang diarahkan langsung untuk mengatasi permasalahan lingkungan, kecuali kegiatan yang dipersiapkan oleh PBB, seperti promosi World Environment Day dan East Asia Sea (EAS) Plan of Action.
Menurut Wakana Takahashi, Keenam area prioritas ASEP memang dipilih berdasarkan penghitungan akan keuntungan yang dapat diraih oleh ASEAN dan negara-negara anggotanya ketika menjalankan ASEP.[31] Tak dapat dipungkiri, walaupun negara-negara ASEAN menyadari adanya kesamaan kepentingan dalam menghadapi isu lingkungan, kondisi mereka yang merupakan negara berkembang menyebabkan munculnya kepentingan materialistik dalam menghadapi isu tersebut.
Indikasi bahwa kerjasama lingkungan di Asia Tenggara pada tahun 1977-1989 masih didasari oleh keuntungan relatif terlihat terutama dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui ASEP-I dan ASEP-II. Jika melihat Tabel 2 pada bagian Kronologi Kerjasama Lingkungan Asia Tenggara, maka kita akan menemukan bahwa ASEP lebih berfokus pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya negara-negara ASEAN (Cont: pengembangan jaringan regional ASEAN untuk menghadapi isu lingkungan, Transfer teknologi organo-industrial pollution control, berbagai jenis pelatihan). Tidak ada satu pun kegiatan ASEP-I dan ASEP-II yang diarahkan langsung untuk mengatasi permasalahan lingkungan, kecuali kegiatan yang dipersiapkan oleh PBB, seperti promosi World Environment Day dan East Asia Sea (EAS) Plan of Action.
Menurut Wakana Takahashi, Keenam area prioritas ASEP memang dipilih berdasarkan penghitungan akan keuntungan yang dapat diraih oleh ASEAN dan negara-negara anggotanya ketika menjalankan ASEP.[31] Tak dapat dipungkiri, walaupun negara-negara ASEAN menyadari adanya kesamaan kepentingan dalam menghadapi isu lingkungan, kondisi mereka yang merupakan negara berkembang menyebabkan munculnya kepentingan materialistik dalam menghadapi isu tersebut.
Menurut Lorraine Elliot, salah satu kepentingan materialistik negara-negara ASEAN dalam pengimplementasian program ASEP adalah mendapatkan teknologi atau keahlian yang dapat membantu mereka mempertahankan keberlangsungan sumber daya alamnya.[32] Bahkan, ASEAN tidak terlihat berusaha menutupi kepentingan materialistiknya di dalam pernyataan Manila Declaration on ASEAN Environment yang dirangkum oleh Weatherbee[33]. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan pengimplementasian ASEP bukanlah didasarkan pada keinginan untuk mengatasi persoalan lingkungan, namun lebih didasarkan pada keuntungan relatif yang akan diraih oleh negara-negara ASEAN ketika mengimplementasikannya.
Jadi, pada tahun 1977-1989, interaksi terkait isu lingkungan di Asia Tenggara sudah mulai tercipta dan intensitasnya terus meningkat, sehingga tercipta sebuah sistem sosial yang bersifat informal. Namun, perasaan regionness yang tercipta dari interaksi tersebut masih berada di level rendah karena masih bersifat informal dan didasari oleh kepentingan nasional dan keuntungan relatif. Semua hal tersebut merupakan elemen dari regional complex, sehingga dapat disimpulkan bahwa fase kedua dalam regionalisme isu lingkungan di Asia Tenggara berlangsung dari tahun 1977-1989.
Jadi, pada tahun 1977-1989, interaksi terkait isu lingkungan di Asia Tenggara sudah mulai tercipta dan intensitasnya terus meningkat, sehingga tercipta sebuah sistem sosial yang bersifat informal. Namun, perasaan regionness yang tercipta dari interaksi tersebut masih berada di level rendah karena masih bersifat informal dan didasari oleh kepentingan nasional dan keuntungan relatif. Semua hal tersebut merupakan elemen dari regional complex, sehingga dapat disimpulkan bahwa fase kedua dalam regionalisme isu lingkungan di Asia Tenggara berlangsung dari tahun 1977-1989.
Fase Ketiga
Fase ketiga dari regionalisme isu lingkungan di Asia Tenggara berlangsung semenjak tahun 1989. Tahun tersebut menjadi titik awal dari fase ketiga karena di tahun tersebut untuk pertama kalinya dibuat struktur institusi yang jelas terkait kerjasama lingkungan di Asia Tenggara dan bersifat mengikat setiap negara anggota ASEAN dengam memberikan mereka tugas-tugas yang spesifik.
Struktur ini memungkinkan terciptanya kerjasama lingkungan yang lebih terorganisir serta mampu memfasilitasi proses pembuatan peraturan yang bersifat formal dalam kerjasama tersebut. Selain itu, struktur organisasi yang bersifat hierarkis ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN sudah merasa nyaman untuk bekerja di bawah negara lain. Hal ini mengindikasikan adanya rasa saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN dalam kerjasama lingkungannya.
Beberapa program atau deklarasi yang dihasilkan dari kerjasama lingkungan setelah tahun 1989 sudah tidak lagi dibuat hanya karena kepentingan nasional atau keuntungan relatif, melainkan juga karena adanya kepentingan transnasional yang teridentifikasi pada tahun 1991. Krisis asap tahun 1991 merupakan sebuah pukulan keras bagi keegoisan negara-negara ASEAN. Polusi (udara maupun laut) merupakan sebuah peristiwa yang tidak dapat dikerangkeng dalam garis imajiner teritori negara.
Beberapa program atau deklarasi yang dihasilkan dari kerjasama lingkungan setelah tahun 1989 sudah tidak lagi dibuat hanya karena kepentingan nasional atau keuntungan relatif, melainkan juga karena adanya kepentingan transnasional yang teridentifikasi pada tahun 1991. Krisis asap tahun 1991 merupakan sebuah pukulan keras bagi keegoisan negara-negara ASEAN. Polusi (udara maupun laut) merupakan sebuah peristiwa yang tidak dapat dikerangkeng dalam garis imajiner teritori negara.
Loraine Elliot menjelaskan bahwa peristiwa tersebut menantang negara-negara ASEAN untuk tidak hanya berpikir akan dampak domestik yang akan dirasakan oleh mereka saja, melainkan juga dampak yang akan dirasakan oleh negara-negara di sekitarnya.[34] Dengan demikian, terdapat kejelasan mengenai apa sesungguhnya kepentingan bersama atau kepentingan transnasional dari anggota ASEAN terkait isu lingkungan di Asia Tenggara. Kepentingan tersebut telah tertulis secara eksplisit dalam ASEAN Vision 2020. ACPTP, HNPA, dan SPAE merupakan contoh program yang dibuat dengan mengartikulasikan kepentingan transnasional tersebut.
Jadi, intensitas interaksi terkait isu lingkungan di Asia Tenggara semenjak tahun 1989 telah menciptakan perasaan regionness pada tingkat yang lebih tinggi daripada tahun 1977-1989. Regionness tersebut mengubah Asia Tenggara menjadi sebuah masyarakat dimana hubungan di antara anggotanya tidak lagi hanya didasari oleh kepentingan nasional atau keuntungan relatif, melainkan juga karena adanya rasa saling percaya dan kepentingan transnasional yang dibela bersama.
Jadi, intensitas interaksi terkait isu lingkungan di Asia Tenggara semenjak tahun 1989 telah menciptakan perasaan regionness pada tingkat yang lebih tinggi daripada tahun 1977-1989. Regionness tersebut mengubah Asia Tenggara menjadi sebuah masyarakat dimana hubungan di antara anggotanya tidak lagi hanya didasari oleh kepentingan nasional atau keuntungan relatif, melainkan juga karena adanya rasa saling percaya dan kepentingan transnasional yang dibela bersama.
Ditambah lagi, telah tercipta sebuah struktur institusi yang mengatur bagaimana anggota masyarakat tersebut berinteraksi satu sama lain. Namun, sampai tahun 2000, belum ada satu pun kasus yang menunjukkan bahwa telah terdapat identitas yang dimiliki bersama oleh masyarakat Asia Tenggara yang membedakannya dengan masyarakat di kawasan lain. Semua hal tersebut merupakan elemen dari regional society, sehingga dapat disimpulkan bahwa fase ketiga dari regionalisme isu lingkungan di Asia Tenggara berlangsung dari tahun 1989.
Kemungkinan Fase Keempat
Analisis empirik terhadap kronologi kerjasama lingkungan Asia Tenggara dari tahun 1977-2000 masih belum menemukan elemen dari fase keempat regionalisme. Permasalahannya adalah karena belum ditemukan kasus yang menunjukkan bagaimana masyarakat Asia Tenggara telah memiliki satu identitas khusus terkait isu lingkungan yang membedakannya dengan kawasan lain.
Namun, salah satu pernyataan dalam ASEAN Vision 2020 yang berbunyi, “Menciptakan Asia Tenggara yang memiliki seperangkat peraturan dan langkah-langkah kerjasama untuk mengatasi permasalahan yang hanya dapat ditemui dalam skala regional” membuka kemungkinan bagi terciptanya identitas ASEAN terkait isu lingkungan di masa depan. Sebab seperangkat peraturan dan langkah-langkah kerjasama yang disebutkan dalam pernyataan tersebut tentunya akan disesuaikan dengan norma-norma ASEAN Way yang eksklusif melekat pada ASEAN.
Dengan begitu akan tercipta seperangkat peraturan dan langkah-langkah kerjasama unik yang hanya ada di Asia Tenggara. Hal tersebut tentunya akan menjadi semacam identitas sendiri bagi ASEAN yang akan membuka kemungkinan berlangsungnya Fase Keempat regionalisme isu lingkungan di Asia Tenggara.
Berdasarkan studi empirik terhadap kronologi kerjasama lingkungan di Asia Tenggara dari tahun 1977-2000, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan drastis dalam kondisi hubungan internasional di Asia Tenggara terkait isu lingkungan. Perubahan tersebut berlangsung dalam tiga fase.
Kesimpulan
Berdasarkan studi empirik terhadap kronologi kerjasama lingkungan di Asia Tenggara dari tahun 1977-2000, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan drastis dalam kondisi hubungan internasional di Asia Tenggara terkait isu lingkungan. Perubahan tersebut berlangsung dalam tiga fase.
Fase pertama dimana hanya ada sebuah wilayah, fase kedua dimana wilayah tersebut berubah menjadi sistem sosial, dan fase ketiga dimana sistem sosial tersebut berubah lagi menjadi masyarakat. Perubahan ini merupakan bagian dari proses regionalisme yang dipahami sebagai sebuah proses dimana entitas geografis bertransformasi dari sekedar objek pasif menjadi subjek aktif yang mampu untuk mengartikulasikan kepentingan transnasional dari kawasan itu sendiri.
Asia Tenggara memang hanya sekedar wilayah yang di dalamnya terdapat orang-orang yang tinggal berdekatan dan berbagi sumber daya alam yang sama. Namun, proses regionalisme yang terjadi di wilayah tersebut mengakibatkan Asia Tenggara bertransformasi menjadi sebuah sistem sosial kemudian masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan kepentingan kawasan tersebut. Dalam hal ini, kepentingan tersebut adalah untuk melindungi orang-orang Asia Tenggara dari dampak buruk lingkungan.
Fase keempat dimana masyarakat tadi bertransformasi menjadi sebuah komunitas memang masih belum ditemukan dari studi empirik ini. Namun, pernyataan dalam ASEAN Vision 2020 membuka kemungkinan tersebut. Selain itu, beberapa kasus yang terjadi setelah tahun 2000 dapat menjadi data yang berguna untuk meneliti fase keempat dalam regionalisme isu lingkungan di Asia Tenggara.
Fase keempat dimana masyarakat tadi bertransformasi menjadi sebuah komunitas memang masih belum ditemukan dari studi empirik ini. Namun, pernyataan dalam ASEAN Vision 2020 membuka kemungkinan tersebut. Selain itu, beberapa kasus yang terjadi setelah tahun 2000 dapat menjadi data yang berguna untuk meneliti fase keempat dalam regionalisme isu lingkungan di Asia Tenggara.
Contohnya adalah pembuatan ASEAN Socio-Cultural Community dimana AMME akan menjadi badan di bawahnya. Ke depannya, studi mengenai regionalisme isu lingkungan di Asia Tenggara harus diarahkan untuk menemukan faktor-faktor yang dapat membantu berlangsungnya fase keempat. Dengan begitu, isu lingkungan akan mendapatkan tempat yang lebih pantas untuk berkembang.
[1] Romeo M. Bautista dan Dean A.
DeRosa, “Agriculture and the New Industrial Revolution in Asia,”
TMD Discussion Paper Vol. 13 (1996):
2.
[2] Philip Hirsch dan Carol Warren,
“Introduction: through the environmental looking glass: the politics of
resources and resistance in Southeast Asia,” dalam The Politics of Environment in Southeast Asia: Resource and Resistance,
ed. Philip Hirsch dan Carol Warren (Routledge, 1998), 5.
[3] James Cotton, “ASEAN and
Southeas Asian ‘Haze’: Challanging the Prevailing Modes of Regional Engagement,”
Working Paper No. 1999/3 (NUS, 1999):
2-5
[4] Uttara Sahasrabuddhe,
“Regionalisation Process in South and Southeast Asia: A Comparative Study,” Asian Scholarship,
www.asianscholarship.org/asf/ejourn/articles/Sahasrabuddhe.pdf (diakses pada 16 Mei 2013).
[5] Björn Hettne dan Fredrik
Söderbaum, “Theorizing the Rise of Regionness,” dipresentasikan dalam 3rd
Annual Conference After the Global
Crises: What Next for Regionalism (1999): 10-18.
[6] Ibid, 9.
[7] Uttara Sahasrabuddhe, “Regionalisation
Process in South and Southeast Asia: A Comparative Study,” Asian Scholarship,
www.asianscholarship.org/asf/ejourn/articles/Sahasrabuddhe.pdf (diakses pada 16 Mei 2013).
[8] Kelima negara tersebut termasuk
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand
[9] Wakana Takahashi, “Environmental Cooperation in Southeast
Asia,” Institute for Global Environmental
Strategies (2000): 1, enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/1705/attach/seasia.pdf (diakses pada 13 Mei 2013).
[10] Lorraine Elliott, “ASEAN and
Environmental Cooperation: Norms, Interests, and Identity,” The Pacific Review, Vol. 16 No. 1,
(Routledge:2003),: 38.
[11] ASEAN Expert Group on the
Environment (AEGE) adalah sebuah badan yang terdiri dari ahli-ahli lingkungan
dari negara-negara anggota ASEAN yang mengadakan pertemuan setiap setahun
sekali di bawah komando ASEAN Committee on Science and Technology (COST). AEGE berfungsi
sebagai badan pembuat keputusan yang juga melakukan review dan pengembangan terkait usaha-usaha ASEAN dalam menghadapi
isu-isu lingkungannya. Lebih lanjut baca: Wakana Takahashi, “Environmental Cooperation in Southeast Asia,” Institute for Global Environmental Strategies (2000): 1, enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/1705/attach/seasia.pdf (diakses pada 13 Mei 2013).
[12] Wakana Takahashi, Ibid.
[13] ASEAN Ministerial Meeting on
Environment (AMME) adalah pertemuan setingkat menteri yang dilaksanakan dalam
kurun waktu tiga tahun sekali untuk membahas isu-isu terkait lingkungan di
ASEAN. Pertemuan ini merupakan badan pembuat keputusan utama ASEAN untuk
menghadapi isu-isu lingkungannya. Seluruh deklarasi dan perjanjian yang
diadopsi oleh AMME telah mendefinisikan prinsip, tujuan, dan praktik penanganan
isu lingkungan bagi negara-negara anggota ASEAN. Lebih lanjut baca: Lorraine
Elliott, “ASEAN and Environmental Cooperation: Norms, Interests, and Identity,”
The Pacific Review, Vol. 16 No. 1,
(Routledge:2003): 36.
[14] Donald E. Weatherbee, International Relations in Southeast Asia,
(Rowman & Littlefield:2009), 275.
[15] Pada waktu itu, Brunei
Darussalam telah bergabung ke dalam ASEAN, sehingga negara anggota ASEAN
menjadi berjumlah enam
[16] Lorraine Elliott, “ASEAN and
Environmental Cooperation: Norms, Interests, and Identity,” The Pacific Review, Vol. 16 No. 1,
(Routledge:2003): 39.
[17] Strengthening Environmental Compliance and Law in Indonesia: Towards
Improved Environmental Stringency and Environmental Performance,
(IDLO:2005): 5.
[18] Lorraine Elliott, “ASEAN and
Environmental Cooperation: Norms, Interests, and Identity,” The Pacific Review, Vol. 16 No. 1,
(Routledge:2003): 39.
[19] Negara yang tidak meratifikasi
ACNNR adalah Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, lebih lanjut baca:
Kheng-Lian Koh, “Asean Agreement on the Conservation of Nature and Natural
Resources, 1985: A Study in Environmental Governance,” dipresentasikan dalam World Parks Congress 2003 (Durban,
September 2003).
[20] Wakana Takahashi, “Environmental Cooperation in Southeast
Asia,” Institute for Global Environmental
Strategies (2000): 1, enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/1705/attach/seasia.pdf (diakses pada 13 Mei 2013).
[21] Second ASEAN State of the Environment Report 2000, (ASEAN:2000): 164.
[22] Ibid.
[23] Wakana Takahashi, “Environmental Cooperation in Southeast
Asia,” Institute for Global Environmental
Strategies (2000): 1, enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/1705/attach/seasia.pdf (diakses pada 13 Mei 2013).
[24]
“ASEAN Vision 2020,” ASEAN, www.asean.org/news/item/asean-vision-2020
(diakses pada 17 Februari 2015)
[25] Lorraine Elliott, “ASEAN and
Environmental Cooperation: Norms, Interests, and Identity,” The Pacific Review, Vol. 16 No. 1,
(Routledge:2003),: 43-44.
[26] Donald E. Weatherbee, International
Relations in Southeast Asia, (Rowman & Littlefield:2009), 281-291.
[27] Lorraine Elliott, “ASEAN and
Environmental Cooperation: Norms, Interests, and Identity,” The Pacific Review, Vol. 16 No. 1,
(Routledge:2003): 39.
[28] Ibid, 38.
[29] Chee Yoke Ling, The Rio Declaration on Environment and Development: An Assessment,
(TWN:2012): 2
[30] Emmanuel Yap, The
Politics of Environment in Southeast Asia: Resource and Resistance,
(Routledge:1998), 285.
[31] Wakana Takahashi, Environmental Cooperation in Southeast
Asia, 2, diakses dari: enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/1705/attach/seasia.pdf
pada 13 Mei 2013 pukul 14:42.
[32] Lorraine Elliott, “ASEAN and
Environmental Cooperation: Norms, Interests, and Identity,” The Pacific Review, Vol. 16 No. 1, (Routledge:2003), 38.
[33] Rangkuman Manila Declaration on
Environment oleh Weatherbee: “Kepentingan
bersama ASEAN dalam menghadapi isu lingkungan terkait dengan adanya kebutuhan
untuk memastikan perlindungan terhadap lingkungan ASEAN dan kesinambungan sumber
daya alamnya agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan di negara-negara ASEAN.”
Lebih lanjut lihat Donald E. Weatherbee,
“Environmental Issues in International Relations in Southeast Asia,” International Relations in Southeast Asia,
(Rowman & Littlefield:2009), 275.
[34] Lorraine Elliott, “ASEAN and
Environmental Cooperation: Norms, Interests, and Identity,” The Pacific Review, Vol. 16 No. 1,
(Routledge:2003), 38.


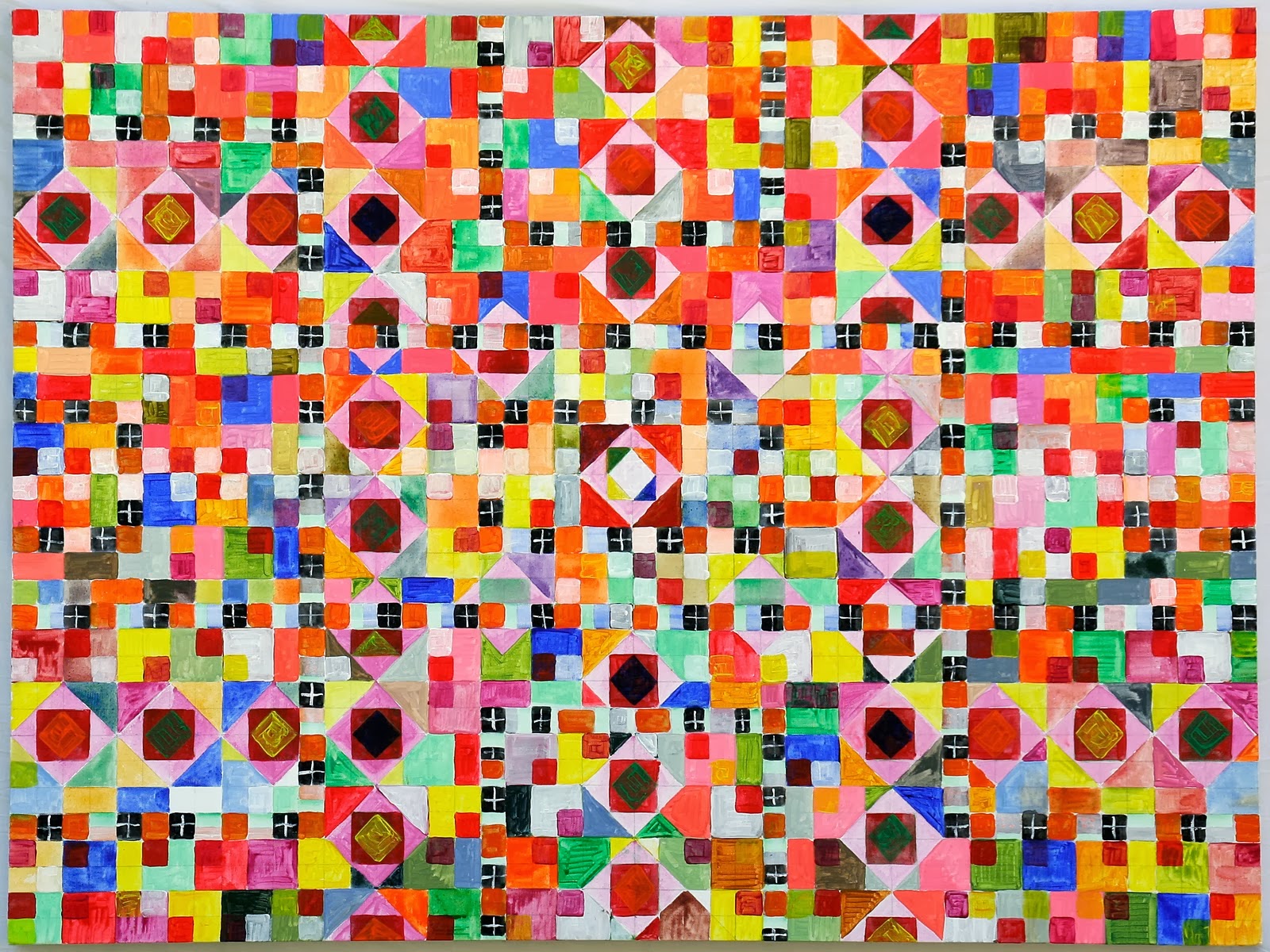



Comments
Post a Comment